 Memakai Jilbab adalah syari’at. Hanya satu yang tidak mensyari’atkan jilbab, bukan Islam.
Memakai Jilbab adalah syari’at. Hanya satu yang tidak mensyari’atkan jilbab, bukan Islam.(Pk Wahyudin. Dosen PAI Fak. Ekonomi Unsoed)
Tentu kita tahu bahwa pluralitas adalah realita tak terbantahkan bagi Indonesia, bahkan di ruang yang paling kecilpun tetap tidak ada yang namanya identik. Begitupun Founding Fathers bangsa kita rupanya sudah memahami betul akan kebinekaan bagi Indonesia, dipilihnya Pancasila ‘Bhineka Tunggal Eka’ sebagai dasar negara dan mereka juga tidak gegabah seperti orde baru yang membatasi agama cukup lima.
Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman, sebagai sebuah lembaga pendidikan milik negara penganut welfare State yang menjamin pendidikan warga negaranya jelas memiliki konsekuensi harus menerima berbagai perbedaan dan tetap menjamin kebutuhan pokok seperti pendidikan menjadi hak warganya tanpa pandang bulu, siapa dan penganut aliran apapun. Hal serupa juga harusnya tertanam di kelas Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI), perbedaan pendapat tentang syari’at pastinya tidak membatasi ruangan tersebut.
Kepada Profetika, Pak Wahyudin selaku dosen PAI mengaku bahwa ia mewajibkan Jilbab di kelasnya, dengan alasan adalah kewajiban diri seorang dosen muslim dan menganggap bahwa ”Memakai Jilbab adalah syari’at. Hanya satu yang tidak mensyari’atkan jilbab, bukan islam”. Baginya kelas PAI bukanlah ruang publik, melainkan ruang khusus bagi pemeluk agama islam, sekalipun tanpa melihat lebih bahwa dalam islam terjadi perbedaan pendapat tentang Jilbab sebagai syari’at atau sebuah budaya. Generalisasinya yang cukup gegabah, menganggap bahwa yang tidak mensyari’atkan jilbab bukanlah islam, mendasarinya untuk tanpa ragu mewajibkan jilbab setiap mahasiswinya
Berbeda dengan Qurais Shihab, kearifannya melihat dinamisasi dalam islam tercermin melaui bukunya “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” dengan mengisyaratkan bahwa jilbab masih ikhtilaf (terjadi ragam pendapat). Perkembangan islam yang tidak sekedar membentuk spiritualitas kepada tuhannya namun juga membentuk numerologi atau hubungan antar manusia (Hablum minannas), jelas akan berbeda pada setiap dimensi waktu maupun ruang. Imposible, sebuah pola kehidupan sekarang sama persis dengan pola kehidupan masa mendatang, dan tidak mungkin Indonesia bergeografis tropis akan berkehidupan sama dengan Arab yang berpadangpasir. Fluiditas (kelenturan) sebuah peradaban akan selalu terjadi ketika bertemu dengan sebuah kondisi yang berbeda dengan sebelumnya, terlebih sebagai makhluk berakal budi tentu manusia menjalani waktu hidupnya dengan penuh dinamisasi.
Lebih tepatnya, “Universitas bukanlah tempat penataran!” menurut Abdul Munir Mulkhan, guru besar di Universitas Islam Negeri Jogjakarta ketika wawancara di KBR 68H Jakarta. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa sesungguhnya sebuah perguruan tinggi dibangun dan dipelihara untuk mengembangkan tingkat intelektualitas. Salah satu bentuk intelektualitas itu adalah lewat berpikir kritis. Perlu adanya public sphere yang bersifat netral sehingga tercipta sebuah dialektika yang diikuti oleh berbagai kalangan yang berbeda untuk berdialog, mencipta karya kritis. Bukan kemudian melakukan konfrontasi dalam bentuk penjajahan netralitas ruang kuliah, yang pada akhirnya menghasilkan para mahasiswa wujûduhu ka`adamihi (wujudnya seperti tidak berwujud).
Realitanya seperti sebuah paradoks, saat Unversitas dicita-citakan menghasilkan kaum intelektual kritis; Pak Wahyudin dikelasnya justru melakukan pemburaman immune (netralitas) ruang kuliah dengan pewajiban jilbabnya. Ketika Profetika menanyakan apakah bapak tahu aliran keagaman masing-masing mahasiswa bapak? “tidak tahu, wallahualam bissawab” Jawabnya. Artinya, secara tidak langsung dia tidak bisa menjamin adanya kesamaan pandangan dalam kelas tersebut atau dengan kata lain, ruangan tersebut masih dibilang ruang publik, sekalipun parsial sesama muslim. Hanya karena generalisasinyalah — yang tidak mensyari’atkan jilbab adalah bukan islam– tidak searif Qurais Shihab tentang jilbab masih ikhtilaf, kemudian Pak Wahyudin menjajah ruang publik tersebut.
Bukan sebuah masalah ketika pewajiban tersebut bersifat pribadi, tidak membawa dampak akademik dan mengatasnamakan ruang kuliah, atau hingga mahasiswinya tertekan secara psikologis. Namun, sekalipun dia tidak menyiratkan bahwa pemakaian jilbab tidak berpengaruh pada nilai, sebuah jawaban retoris justru disampaikannya kepada Profetika “Allah saja memberi pahala kepada hambanya yang taat, apalagi saya”. Ditambah lagi melihat kenyataan banyak mahasiswinya yang lepas jilbab setelah kuliahnya-pun belum mampu ia jawab; apakah karena nilai atau yang lainnya.
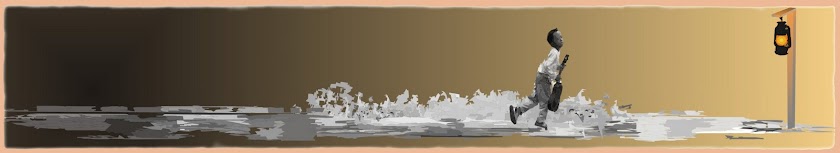
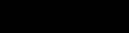



Tidak ada komentar:
Posting Komentar